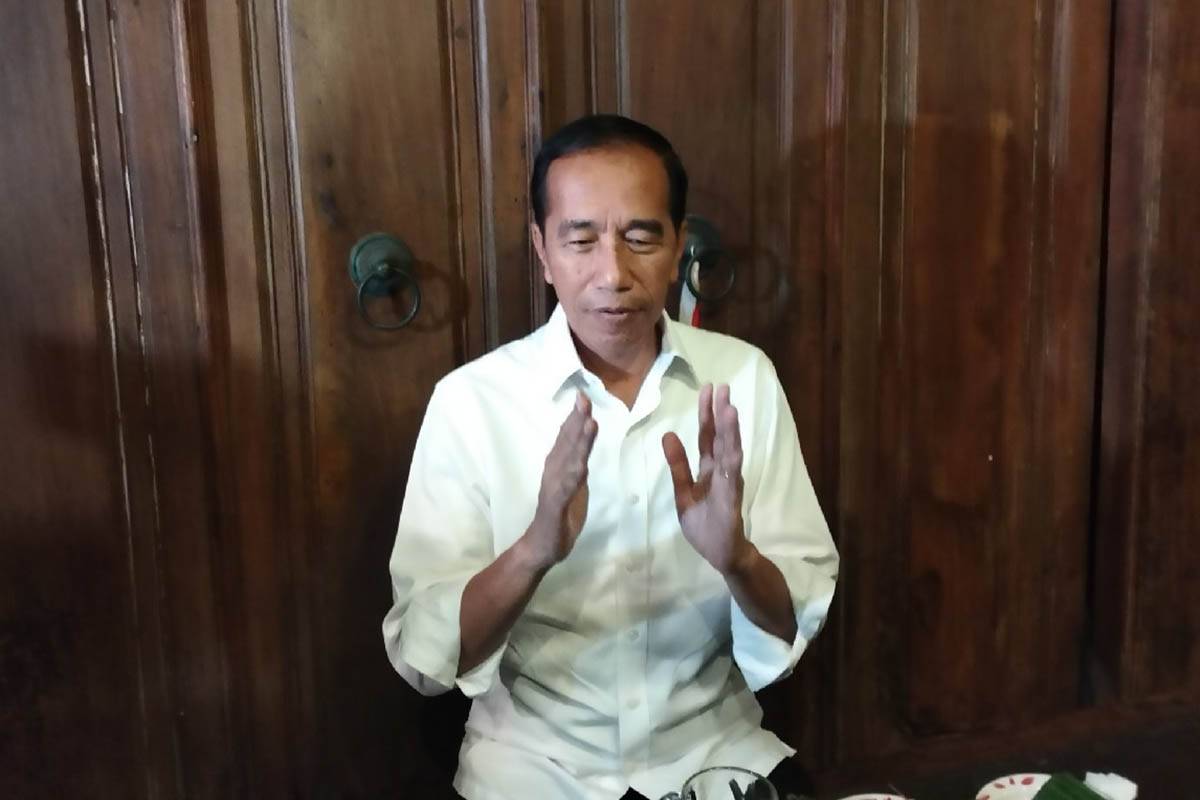Di sudut kota kecil yang tak banyak disorot media, tinggal seorang ibu bernama Bu Lastri, jurnalis lepas di usia senjanya. Dulu ia dikenal sebagai penulis tajam, suaranya kerap menggema lewat tulisan-tulisannya yang membela kaum kecil. Kini, hanya meja kecil, laptop tua, dan secangkir kopi dingin yang menjadi teman setianya.
Sejak suaminya meninggal lima tahun lalu, Bu Lastri hidup berdua bersama anak bungsunya, Dani. Sedangkan anak sulungnya, Dinda, telah menikah dan tinggal di Jakarta bersama suaminya. Sejak pernikahan itu, Dinda jarang pulang. Alasan klasik: sibuk. Bahkan pesan singkat pun mulai menjadi barang langka.
Padahal dulu, Dinda sering berkata, “Ibu inspirasiku. Aku mau jadi kuat seperti Ibu.” Tapi setelah menikah, seakan dunia barunya menenggelamkan semua yang pernah ia ucapkan.
Dani, meski tinggal serumah, punya dunianya sendiri. Ia masih muda, masih suka keluar malam. Meski tak pernah bersikap kasar, namun sikap acuhnya membuat rumah kecil itu terasa lebih sepi dari biasanya.
Bu Lastri masih menulis. Tak setiap hari dimuat, tak selalu dibayar, tapi ia menulis. Tentang ibu-ibu yang berjualan di pasar, tentang anak-anak yang tak sempat sekolah, tentang hidup yang terus berjalan meski tak selalu adil. Ia menulis dengan hati, seperti dulu saat masih penuh semangat.
Kadang, sambil mengetik, ia memandangi foto keluarga yang dipajang di dinding. Senyum Dinda terpampang di sana—muda, cantik, bahagia. Tapi tak ada kabar, tak ada kunjungan, tak ada pelukan.
Malam itu, hujan turun deras. Listrik sempat padam. Di tengah kegelapan, Bu Lastri menyalakan lilin dan membuka draft tulisan terakhirnya.
Judul "Ibu yang Tak Lagi Dirindukan."
Ia menulis:
“Bukan soal uang. Bukan juga soal bantuan. Ini tentang rindu yang tak pernah dianggap penting. Tentang doa yang terus dipanjatkan tanpa tahu apakah anak itu masih mengingat. Seorang ibu tak meminta banyak, hanya ingin didengar. Hanya ingin tahu bahwa dirinya masih berarti.”
Saat selesai mengetik, air matanya jatuh perlahan. Tapi ia tersenyum. Karena dalam setiap kata yang ia tulis, ia masih menjadi ibu—yang mencintai tanpa syarat, yang menunggu tanpa mengeluh, yang bertahan meski dunia sepi.
Dan di tengah badai hidup, di balik kata-kata yang ia ketik sendirian, Bu Lastri tetap berdiri. Seorang jurnalis. Seorang ibu. Yang tidak pernah kehilangan kekuatan, meski perlahan dilupakan.(Lindafang).